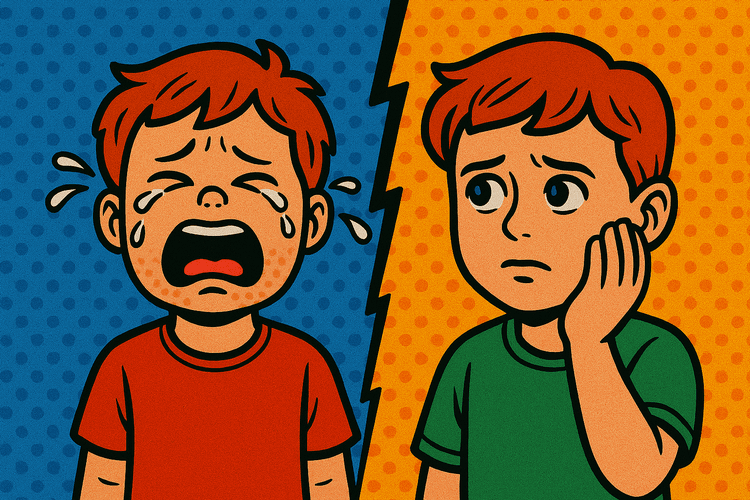
Mungkin Anda pernah berpikir, “Anak saya ini cengeng banget, ya!” atau malah, “Kok gampang banget tersinggung?”
Anda nggak sendirian. Banyak orang tua merasa bingung membedakan antara anak yang cengeng dan anak yang sensitif, padahal sebenarnya dua hal ini beda banget lho!
Menurut studi dari Child Mind Institute, sekitar 15–20% anak termasuk dalam kategori highly sensitive children (HSC).
Ini bukan tanda kelemahan, justru bisa menjadi kekuatan besar dalam hal empati dan pemahaman emosional.
Sayangnya, banyak anak sensitif yang malah keburu diberi label negatif, karena dianggap lemah atau terlalu manja.
Artikel ini membahas soal perbedaan keduanya. Apa sih yang membuat anak disebut cengeng? Apa yang menandakan anak tersebut sebenarnya sangat sensitif?
Dan yang paling penting, bagaimana cara menghadapi keduanya dengan pendekatan yang tepat, tanpa membuat anak merasa tertekan atau tidak dipahami.
Apa Itu Anak Cengeng dan Anak Sensitif?
Anak saya dulu sering menangis karena hal kecil, misalnya karena sendok makannya basah atau bajunya nggak cocok warnanya.
Di kepala saya cuma ada dua label: “anak manja” atau “anak cengeng.”
Tapi makin lama, makin saya sadar… nggak semua tangisan anak itu tanda kelemahan.
Kadang, justru itu bentuk dari kepekaan yang luar biasa.
Secara sederhana, anak cengeng itu biasanya menangis karena hal-hal sepele dan punya kecenderungan untuk overreact.
Misalnya, ketika tidak dibelikan mainan di minimarket, ia langsung guling-guling sambil teriak.
Reaksi ini sering kali bukan karena dia benar-benar sedih, tapi karena belum bisa mengatur emosinya atau sudah terbiasa “menangis = dapat perhatian.”
Tangisnya cenderung manipulatif, meskipun itu bukan salah mereka juga. Mereka masih belajar, kan?
Sementara itu, anak sensitif beda cerita.
Mereka bisa terlihat lebih “tenang,” tapi sekalinya terluka, walau hanya karena dikritik dengan nada tinggi, reaksinya bisa dalam banget.
Saya ingat, anak saya pernah diem aja seharian cuma gara-gara saya bilang, “Ayo cepet, Mama lagi capek.”
Nggak marah, nggak nangis. Tapi sorot matanya berubah.
Dan malamnya, dia bisik pelan, “Mama kayaknya nggak suka sama aku, ya?”
Itu bikin saya langsung sadar, ini bukan anak cengeng. Ini anak yang sensitif secara emosional.
Ia memproses kata dan ekspresi dengan kedalaman yang kadang kita, sebagai orang dewasa, suka anggap remeh.
Kenapa penting bedain dua istilah ini? Karena pendekatannya beda banget.
Kalau kita salah sangka, bisa-bisa malah makin memperburuk keadaan.
Anak cengeng butuh batasan yang jelas dan latihan mengelola emosi.
Tapi anak sensitif? Mereka butuh pengakuan, empati, dan ruang untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi.
Guru pun sering salah paham. Anak yang terlihat “baperan” atau terlalu sensitif di kelas sering dikira lemah mental, padahal dia cuma belum nemu cara sehat buat mengolah rasa.
Saya pernah ngobrol dengan guru TK yang bilang, “Dia terlalu sensitif, sih, jadi bikin suasana kelas jadi ribet.”
Padahal kalau tahu caranya, anak sensitif justru bisa jadi pemimpin emosional dalam kelompok karena peka terhadap perasaan teman-temannya.
Intinya begini: anak cengeng dan anak sensitif sama-sama berhak dimengerti.
Tapi kita, sebagai orang dewasa, harus tahu dulu perbedaannya sebelum bisa bantu mereka tumbuh tanpa mengubah siapa mereka sebenarnya.
Ciri-Ciri Anak Cengeng vs Anak Sensitif
Waktu anak saya berusia sekitar 4 tahun, saya sering dibuat bingung.
Kadang dia nangis gara-gara hal yang menurut saya sepele banget, misalnya saya lupa kasih sedotan di gelasnya, atau karena saya nyuruh dia berhenti main saat waktunya mandi.
Saya sempat mikir, “Apa ini anak cengeng, ya?”
Tapi seiring waktu, saya mulai bisa membedakan mana yang sekadar tangisan manipulatif, dan mana yang muncul dari hati yang sensitif.
Ciri anak cengeng, dari pengalaman saya, biasanya terlihat dari pola tangisnya yang muncul ketika keinginannya nggak dituruti.
Misalnya, ketika nggak dibelikan permen di minimarket, dia langsung menangis, ngambek, bahkan guling-guling di lantai.
Tapi begitu diberi perhatian atau distraksi kecil seperti “Nanti kita beli es krim, ya,” dia langsung diam.
Tangisnya kayak punya tujuan, ingin sesuatu terjadi, dan kalau sudah tercapai, dia tenang.
Anak seperti ini juga biasanya gampang frustrasi saat main puzzle atau balok dan nggak berhasil langsung.
Dia pengennya cepat, instan, dan langsung berhasil.
Di sisi lain, anak sensitif nggak selalu langsung nangis.
Tapi reaksinya lebih dalam dan bertahan lama.
Misalnya, saya pernah tanpa sengaja ngomong, “Kamu ini gimana sih, nggak bisa diem sedikit aja?” saat lagi capek banget.
Dia nggak nangis waktu itu, tapi sorot matanya langsung berubah.
Nggak lama kemudian, dia mulai menghindar, nggak mau peluk, dan malamnya bilang, “Mama marah ya sama aku?”
Saya langsung tahu, ini bukan cengeng, ini anak yang benar-benar peka secara emosional.
Anak sensitif juga sangat empatik. Pernah ada temannya jatuh di taman bermain, dan dia yang ikut nangis karena ngerasa sedih juga.
Kadang mereka juga merasa bersalah berlebihan, walau cuma karena menumpahkan air atau lupa membereskan mainan.
Dan yang paling saya perhatikan: mereka butuh waktu lebih lama buat pulih dari kecewa.
Kalau anak cengeng bisa “lupa” dalam 5 menit asal dikasih cokelat, anak sensitif bisa bawa perasaan itu sampai malam.
Jadi, menurut saya, perbedaan besarnya ada di tujuan dan kedalaman emosinya.
Anak cengeng lebih ke arah respons instan dan manipulatif (tanpa sadar tentunya), sementara anak sensitif lebih reflektif dan berhubungan dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
Kita harus benar-benar memperhatikan konteksnya, kenapa dia menangis, berapa lama, dan apa pemicunya.
Saat kita bisa bedakan dengan jelas ciri-cirinya, kita juga jadi lebih siap kasih respons yang tepat.
Nggak semua tangisan itu butuh solusi. Kadang, mereka cuma butuh dipeluk dan didengar.
Kenapa Anak Bisa Jadi Cengeng atau Sensitif?
Saya dulu sempat dibuat bingung kenapa anak saya gampang banget nangis.
Jatuh sedikit, nangis. Ditegur pelan, nangis. Mainan rusak, bisa drama sampai setengah jam.
Seiring waktu, saya mulai ngerti: ternyata ada banyak alasan kenapa anak bisa jadi cengeng atau sensitif.
Dan bukan semuanya salah anak, lho.
Yang pertama, tentu saja, faktor biologis dan bawaan sejak lahir.
Ada anak yang memang secara genetik lebih peka terhadap rangsangan, baik suara, cahaya, atau emosi orang sekitar.
Bahkan sejak bayi, ada yang sudah kelihatan lebih mudah kaget, susah tidur kalau suasana terlalu ramai, atau rewel kalau rutinitasnya berubah.
Ini bukan karena mereka “rewel,” tapi karena sistem sarafnya memang lebih responsif.
Anak sensitif biasanya punya sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi, yang sangat aktif.
Jadi, ketika dia kecewa atau sedih, perasaannya bisa jauh lebih dalam dari anak lain.
Lalu, ada juga pengaruh pola asuh.
Misalnya, kalau orang tua sering berubah-ubah, hari ini boleh, besok dilarang tanpa penjelasan, anak jadi bingung dan merasa nggak aman.
Atau, kalau orang tua terlalu keras dan nggak memberi ruang untuk anak mengekspresikan perasaan, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang menahan emosi terlalu lama, lalu meledak dalam bentuk tangisan atau tantrum.
Kadang, anak jadi cengeng karena merasa itu satu-satunya cara agar didengar.
Saya pun pernah tanpa sadar melakukan itu, langsung suruh “diam” waktu anak nangis, padahal dia cuma butuh dipahami.
Lingkungan juga sangat berpengaruh. Anak yang tumbuh di lingkungan penuh tekanan, atau tidak pernah diajak bicara soal emosi, bisa kehilangan kemampuan mengelola perasaan secara sehat.
Misalnya, kalau di rumah semua harus “tough” dan nggak boleh nangis, maka ketika anak merasakan kecewa, dia malah bingung sendiri dan menangis secara berlebihan sebagai bentuk frustrasi.
Dan jangan lupakan *trauma atau tekanan yang tersembunyi.
Ada anak yang tampaknya baik-baik saja, tapi ternyata sedang mengalami tekanan di sekolah, mungkin dibully, dimarahi guru, atau kesulitan pelajaran.
Ada juga yang menyimpan trauma kecil yang menurut kita sepele, tapi sangat berkesan buat dia.
Misalnya, pernah tersesat sebentar di supermarket atau dimarahi di depan umum, hal-hal begitu bisa nempel lama banget di hati anak.
Dari pengalaman saya, memahami latar belakang emosi anak itu penting banget.
Jangan buru-buru kasih label. Kadang anak yang terlihat “cengeng” sebenarnya cuma sedang butuh rasa aman.
Dan anak yang “sensitif” bukan berarti lemah, dia hanya butuh lingkungan yang lebih hangat dan bisa memeluk jiwanya.
Kalau kita bisa telusuri akar masalahnya, bukan cuma tangisan anak yang bisa berkurang, tapi juga hubungan kita dengan mereka bisa jauh lebih kuat dan sehat.
Kesalahan Orang Tua dalam Menyikapi Anak Emosional
Dulu saya juga sering melakukan kesalahan ini.
Waktu anak saya mulai sering menangis karena hal-hal yang menurut saya nggak penting, respons pertama saya adalah… menertawakan.
Bukan karena saya nggak sayang, tapi karena saya pikir itu cara yang “ringan” untuk menghadapi dramanya.
Tapi ternyata, dari situlah justru masalahnya makin besar.
Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang tua terhadap anak emosional adalah menyepelekan atau menertawakan tangisannya.
Saya ingat waktu anak saya nangis karena gambarnya robek sedikit, saya bilang, “Ya ampun, masa gitu aja nangis?” Sambil ketawa.
Saya kira itu bisa bikin dia melihat masalahnya dari sisi lucu, tapi yang terjadi justru dia merasa makin sedih.
Dia diam, lalu bilang, “Nggak ada yang ngerti aku.” Dan di situ saya merasa… nyesek.
Labeling juga jadi jebakan berikutnya.
Saat kita bilang, “Kamu tuh drama queen banget deh,” atau “Cengeng banget sih, kayak bayi,” niatnya mungkin buat menyadarkan anak, tapi efeknya?
Mereka mulai percaya label itu.
Anak yang sering dibilang lemah akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang rendah.
Mereka bisa berpikir bahwa emosi mereka adalah sesuatu yang salah.
Padahal menangis itu bukan aib, dan bukan berarti dia tidak kuat.
Kesalahan lain yang sempat saya lakukan adalah menghukum anak karena menangis.
Saya pernah bilang, “Kalau kamu terus nangis, Mama tinggal ya.”
Atau, “Berhenti sekarang juga atau nggak boleh main.”
Dan walaupun itu kadang berhasil bikin dia diam, tapi bukan karena dia belajar mengelola emosi, dia hanya belajar menyembunyikannya.
Anak belajar takut mengekspresikan perasaan, dan itu bisa sangat merusak di masa depan.
Yang paling diam-diam berbahaya adalah menghindari pembicaraan soal perasaan.
Karena sebagai orang tua, kita kadang mikir, “Nanti juga reda sendiri.”
Tapi emosi yang nggak diproses, lama-lama bisa menumpuk.
Saya pernah coba tanya, “Kamu tadi kenapa nangis?” dan anak saya jawab, “Karena aku pikir Mama nggak sayang lagi.”
Bayangin aja kalau saya nggak pernah tanya. Dia bisa simpan pikiran itu terus.
Intinya, anak emosional itu bukan anak yang bermasalah.
Mereka cuma belum tahu cara menyalurkan perasaannya.
Dan tugas kita sebagai orang tua bukan untuk memadamkan tangisannya, tapi untuk mendampingi prosesnya.
Karena emosi bukan musuh, emosi itu sinyal.
Dan kalau kita abaikan sinyal itu, lama-lama hubungan dengan anak jadi renggang, tanpa kita sadar penyebabnya apa.
Sekarang saya belajar untuk lebih sabar, lebih hadir, dan lebih banyak bertanya, “Apa yang kamu rasakan?” dibanding “Kenapa sih kamu nangis terus?”
Dan hasilnya? Anak saya jadi jauh lebih terbuka, dan tangisannya pun… makin jarang.
Cara Menghadapi Anak Cengeng dengan Empati
Banyak orang tua menganggap anak yang sering nangis itu harus “dikuatkan” dengan cara dikerasi.
Ya, biar dia belajar bahwa hidup itu nggak selalu bisa sesuai maunya.
Tapi, cara itu justru bikin anak jadi makin meledak-ledak atau malah menarik diri.
Sampai akhirnya saya belajar tentang satu hal penting: empati.
Dan ternyata, empati itu bukan berarti memanjakan, tapi memahami, sambil tetap memberi batas yang jelas.
Langkah pertama yang cukup ngubah cara saya menghadapi anak cengeng adalah mengajarkan cara menamai emosi.
Bukan cuma bilang, “Kamu marah, ya?” tapi juga ngajarin dia mengenal perasaan seperti kecewa, takut, kesal, malu, atau sedih.
Kadang anak menangis bukan karena kejadian itu besar, tapi karena dia sendiri bingung sama apa yang dia rasakan.
Saya mulai sediakan buku cerita tentang emosi, atau bikin game kecil, “Kalau kamu merasa begini, namanya apa ya?”
Lama-lama dia bisa bilang sendiri, “Aku sedih karena mainanku rusak.” Nah, itu udah luar biasa banget.
Yang juga saya pelajari, dan susah banget di awal adalah tetap tenang dan merespons dengan pelukan, bukan ceramah.
Naluri orang tua biasanya pengen langsung ngomong, “Udah ah, nangis terus, malu dong!”
Tapi waktu saya coba diem dulu, duduk, dan peluk dia sambil bilang, “Mama ngerti kamu lagi kecewa,” reaksinya jauh lebih baik.
Tangisnya cepat reda, dan dia lebih terbuka cerita kenapa tadi nangis. Beneran beda.
Tapi jangan salah, validasi perasaan bukan berarti kita harus selalu ngikutin maunya anak.
Ada kalanya dia tetap nggak boleh nonton TV karena sudah malam, misalnya.
Tapi saya belajar bilang, “Mama tahu kamu kecewa nggak boleh nonton, tapi sekarang waktunya tidur. Kita bisa nonton besok sore, ya.”
Kalimat kayak gitu ngebantu banget karena dia merasa dipahami, walaupun tetap nggak dapet yang dia mau.
Nah, satu teknik lagi yang sangat saya rekomendasikan: ganti time-out jadi time-in.
Dulu saya suka nyuruh dia ke pojokan buat “menenangkan diri.”
Tapi akhirnya saya paham, dia justru merasa dikucilkan.
Sekarang saya ajak dia duduk di pojok tenang bareng saya.
Kadang kami ambil waktu 5 menit, tarik napas bareng, atau gambar bareng sampai dia tenang.
Saya bilang, “Kalau kamu tenang, Mama juga bisa bantu cari solusinya.” Itu ngebangun rasa percaya luar biasa antara kami.
Jadi, buat Anda yang punya anak yang gampang nangis atau terlihat manja, coba deh ganti pendekatan.
Nggak usah buru-buru “mendidik” dengan bentakan atau ancaman.
Coba hadir sebagai pendamping. Anak-anak bukan ingin dimanjakan, mereka ingin dimengerti.
Empati yang kita kasih hari ini, bisa jadi bekal besar untuk kekuatan emosi mereka di masa depan.[]
